
Setengah jam kemudian, Rara dan Amelie sudah berada di bis menuju centrum. Berbeda dengan di Amsterdam, di Maastricht tidak ada tram. Transportasi umum adalah bis dan kereta. Amelie memarkir mobilnya di tempat parkir Maastricht University, lalu mereka membeli karcis bus seharga 2 euro di stasiun bis dekat sana. Setelah menunggu sekitar 15 menit, bis pun datang. Rara dan Amelie memilih tempat duduk di tengah, yang posisinya cukup tinggi. Sangat strategies untuk menikmati kiri-kanan yang tampak cantik. Amelie janjian dengan Martin jam 13, jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jam untuk mereka berjalan-jalan di sekitar centrum.
Saat itu autumn menuju winter. Walaupun cuaca terang, tapi dinginnya tetap menusuk. Turun dari bis, Rara melingkarkan syal abunya lebih ketat pada lehernya. Sungai Maas terpampang indah di depannya. Mereka berjalan sepanjang sungai, lalu menuju Maastrich city hall.


Jalan-jalan di sekitar centrum tampak semakin cantik dengan dekorasi menjelang natal yang satu bulan lagi akan dirayakan. Di depan city hall, banyak pedagang buah dan bunga. Rara membeli buah kesemek kesukaannya, yang disini disebut “kaki fruit”. Harganya 3,5 euro per 10 buah. Sedangkan Amelie, membeli nanas kesukaan om Mark (Om Mark jatuh cinta pada nanas sejak pertama kali mencicipinya di Bandung). Rara juga membeli seikat bunga berwarna orange, ia titipkan pada Amelie untuk diberikan pada Tante Martha. Sebenarnya jarak dari city hall ke Boekhandel Dominicanen sangat dekat, sekitar 3 menit saja berjalan. Tapi mereka melewatinya.


Mereka berjalan melewati Basilica of Saint Servatius yang terkenal dengan bangunan merahnya. Bangunan super tua itu semakin terlihat megah namun anggun. Tanpa harus bersepakat, Amelie dan Rara tau tempat yang dituju kemudian, yaitu Helpoort. Pada jamannya, Helpoort merupakan pintu gerbang masuk ke kota Maastricht dan merupakan salah satu pintu gerbang kota tertua di Belanda. Helpoort adalah pemandangan favorit Rara.






Selama berjalan, dua sahabat itu riang bercerita tentang segala macam hal. Mereka menemukan satu kursi dengan pemandangan helpoort yang cantik di depan mereka. Amelie mebuaka bekalnya : dua roti lapis dan dua apel. “Mau ke Bonnefanten gak?”, Amelie menggoda Rara. Amelie tahu Rara agak “trauma” dengan koleksi yang ia lihat di Bonnefanten Museum. Tiga tahun lalu, waktu Amelie pertama kali mengajak Rara ke rumahnya, sebagai nyonya rumah yang baik ia mengajak Rara ke tempat-tempat yang populer untuk para turis. Salah satunya adalah Museum Bonnefanten. Selama tour, Rara menggamit erat tangan Amelie, dan mengajaknya cepat keluar dari Museum. Malamnya, Rara tidak bisa tidur. “koleksi yang kuliat tadi membuat aku depresi”. Amelie masih ingat kata-kata Rara.




Waktu sudah menunjukkan pukul 12.15. “Hei, cari hot chocolate yuk. Nanti kamu telat ketemu Martin”, Rara mengingatkan. Mereka memilih sebuah cafe yang sepi, dengan kursi yang terbuat dari rotan. Amelie memesan kopi, Rara memesan hot chocolate. “Gak percaya kamu tinggal dua minggu lagi disini”, Amelie berkata. Kalimat pendek dari sahabatnya itu sudah cukup membuat Rara berkaca-kaca. “Sorry, I am so sorry, Aku gak bermaksud bikin kamu sedih”, Amelie kaget dan refleks berpindah tempat ke samping Rara, menggenggam tangan sahabatnya. “Gapapa, bukan salah kamu”, kata Rara berusaha mengendalikan emosinya. “It just… aku ingin menutup hari-hariku di negeri ini dengan kenangan manis. Aku ingin meninggalkan tanah ini dengan senyuman, Amelie”. Amelie memeluk sahabatnya. “Dan sekarang rasanya aku tak bisa. Itulah sebabnya aku merasa dia sangat jahat, Amelie. Dia tidak peduli sama sekali apa yang akan aku rasakan setelah aku mendengar apa yang ia katakan. Dia jahat, Amelie”. Kali ini Rara tak lagi berusaha menahan perasaannya. Ia terguguk dalam pelukan erat sahabatnya. Amelie tidak tahu persis apa yang terjadi, meskipun ia bisa menebaknya samar-samar. Yang ia tahu dengan pasti adalah, saat sahabatnya sudah mengeluarkan isi hatinya, artinya kejadian yang ia alami adalah sesuatu yang “besar”dan “dalam”, yang tak bisa ia simpan sendiri. Rara adalah orang yang paling bisa menyimpan perasaannya dalam-dalam. Hanya orang-orang yang sangat dekat dengannya, yang akan tau apa yang ia rasakan sesungguhnya, itu pun kalau Rara sudah siap mengungkapkannya.
“What exactly did he tell you, Rara?” akhirnya Amelie tidak tahan. Melihat sahabatnya begitu terluka, ia jadi ragu pada tebakannya. “He… he.. he told me… “ Rara melepas pelukan sahabatnya, mengambil tisue, menghapus air matanya, berusaha menenangkan diri, menyeruput hot chocolatenya. Dua sahabat itu saling menatap. “He told me, he want to spend the rest of his life with me”, tangis Rara pecah lagi di ujung kalimat. Dua sahabat itu berpelukan lagi. Rara menangis lebih hebat dari sebelumnya. Kali ini Amelie mengerti. Ia peluk sahabatnya seerat yang ia bisa. Sahabatnya memang mengalami patah hati yang amat parah. Bukan, bukan seperti patah hati yang biasanya orang lain rasakan. Semua laki-laki di dunia boleh mengatakan kalimat “I want to spend the rest of my life with you” untuk merayu, atau untuk mengungkapkan cintanya. Tapi ketika kalimat itu diucapkan oleh laki-laki Belanda, itu bukan main-main. Apalagi jika kalimat itu diucapkan oleh Jeroen, laki-laki super serius itu. Kalimat itu adalah gabungan cinta yang dalam dan komitmen yang kuat. Dan bagian rumitnya adalah, Amelie tahu betapa dalam pula cinta Rara pada laki-laki itu. Namun, semesta tak berpihak pada mereka, dan rasanya tak akan pernah berpihak. Kini air matanya Amelie pun ikut menetes.


 Rara dan Amelie menyiapkan sarapan. Kentang rebus, ayam panggang dan tumis bayam yang ditaburi “pijnboom pitten“. Sambil makan, Amelie bertanya: “Rara, what will you do today? kamu masih perlu sendirian?” . “Aku belum punya rencana apapun”, jawab Rara. “Aku ada janji dengan Martin di Boekhandel Dominicanen buat cari kado buat Mama Martha. Trus kayaknya menginap di rumah Martin. Besok ultah Mama Martha. Kamu mau ikut gak?” Mama Martha yang dimaksud Amelie adalah mamanya Martin, calon mertua Amelie. Tante Martha dan Tante Imke adalah sahabat baik. Percaya atau tidak, pertunangan Amelie dan Martin adalah hasil perjodohan Tante Martha dan Tante Imke. Rara masih ingat bagaimana dua tahun lalu Amelie berusaha menumbuhkan cinta pada pemuda canggung super jangkung yang berprofesi sebagai pengacara itu. Syukurlah cinta itu perlahan tumbuh, sehingga tepat seminggu sebelum tante Imke wafat tahun lalu, pertunangan mereka dilaksanakan, tanpa paksaan dan penuh cinta.
Rara dan Amelie menyiapkan sarapan. Kentang rebus, ayam panggang dan tumis bayam yang ditaburi “pijnboom pitten“. Sambil makan, Amelie bertanya: “Rara, what will you do today? kamu masih perlu sendirian?” . “Aku belum punya rencana apapun”, jawab Rara. “Aku ada janji dengan Martin di Boekhandel Dominicanen buat cari kado buat Mama Martha. Trus kayaknya menginap di rumah Martin. Besok ultah Mama Martha. Kamu mau ikut gak?” Mama Martha yang dimaksud Amelie adalah mamanya Martin, calon mertua Amelie. Tante Martha dan Tante Imke adalah sahabat baik. Percaya atau tidak, pertunangan Amelie dan Martin adalah hasil perjodohan Tante Martha dan Tante Imke. Rara masih ingat bagaimana dua tahun lalu Amelie berusaha menumbuhkan cinta pada pemuda canggung super jangkung yang berprofesi sebagai pengacara itu. Syukurlah cinta itu perlahan tumbuh, sehingga tepat seminggu sebelum tante Imke wafat tahun lalu, pertunangan mereka dilaksanakan, tanpa paksaan dan penuh cinta.
 Kereta berhenti, dengan pemberitahuan sudah sampai di stasiun Maastricht. Ia hanya membawa ransel abu yang setia menemaninya. Meskipun mungkin akan menginap beberapa hari di rumah Amelie, mana sempat tadi ia pulang ke apartmentnya. Kalimat Amelie tadi seperti hipnotis baginya. “Kamu naik intercity jam 16.30an dari Amsterdam Zuid, jam 19 aku jemput di stasiun Maastricht”. Begitu Rara melihat aplikasi 9292nya, dia tersenyum. Perintah Amelie sangat akurat. Ada kereta menuju Maastricht bertolak jam 16.26 dari Platform 2 Amsterdam Zuid.
Kereta berhenti, dengan pemberitahuan sudah sampai di stasiun Maastricht. Ia hanya membawa ransel abu yang setia menemaninya. Meskipun mungkin akan menginap beberapa hari di rumah Amelie, mana sempat tadi ia pulang ke apartmentnya. Kalimat Amelie tadi seperti hipnotis baginya. “Kamu naik intercity jam 16.30an dari Amsterdam Zuid, jam 19 aku jemput di stasiun Maastricht”. Begitu Rara melihat aplikasi 9292nya, dia tersenyum. Perintah Amelie sangat akurat. Ada kereta menuju Maastricht bertolak jam 16.26 dari Platform 2 Amsterdam Zuid.




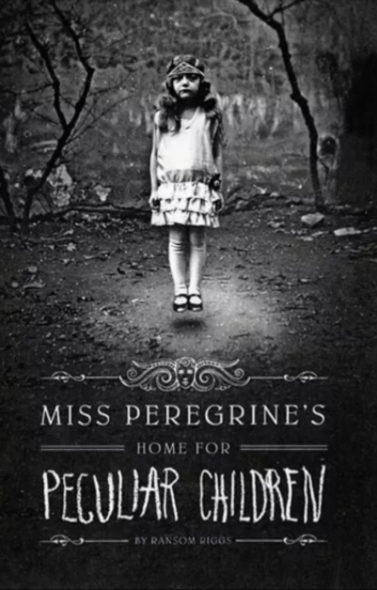 Beberapa tahun yang lalu, saya dan anak-anak menonton film seru berjudul Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Anak-anak lalu bilang, ada bukunya. Kita pun hunting. Di sebuah toko buku, dapat buku tersebut dan buku lanjutannya : Hollow City. Berbahasa Inggris British uy… saya terseok2 bacanya. Jauh lebih susah dibanding English Amerika kalau buat saya mah. Seperti biasa, meskipun udah nonton film-nya, tapi membaca rangkaian kalimat di buku jauh lebih seru. Tapi ternyata, ada yang lebih seru lagi. Cerita di balik proses penulisan novel yang menjadi #1 New York Times best seller tersebut. Ransom Riggs, penulis buku ini, menulis rangkaian cerita di buku ini berdasarkan foto-foto yang ia punya. “The photo came first, and then I shaped the story around the imagery” katanya. Keyen dan kreatif !
Beberapa tahun yang lalu, saya dan anak-anak menonton film seru berjudul Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Anak-anak lalu bilang, ada bukunya. Kita pun hunting. Di sebuah toko buku, dapat buku tersebut dan buku lanjutannya : Hollow City. Berbahasa Inggris British uy… saya terseok2 bacanya. Jauh lebih susah dibanding English Amerika kalau buat saya mah. Seperti biasa, meskipun udah nonton film-nya, tapi membaca rangkaian kalimat di buku jauh lebih seru. Tapi ternyata, ada yang lebih seru lagi. Cerita di balik proses penulisan novel yang menjadi #1 New York Times best seller tersebut. Ransom Riggs, penulis buku ini, menulis rangkaian cerita di buku ini berdasarkan foto-foto yang ia punya. “The photo came first, and then I shaped the story around the imagery” katanya. Keyen dan kreatif ! Setelah 3 bulan berlalu, ada suatu kejadian yang membuat saya dapat wangsit untuk alur ceritanya haha…. Maka, mari kita mulai new adventure ini. Resmilah blog saya nambah satu category berjudul : Tulips from Amsterdam. Konon, life begin at 40. Mungkin “life” yang dimaksud adalah “brave to try something new”. Tapi seperti biasanya, I do it for my self. Sebagai salah satu tambahan coping kalau lagi stress. Jadi ceritanya akan dibuat cerbung dengan waktu tayang menggunakan rumus “saka” : sakainget, sakahoyong 😉
Setelah 3 bulan berlalu, ada suatu kejadian yang membuat saya dapat wangsit untuk alur ceritanya haha…. Maka, mari kita mulai new adventure ini. Resmilah blog saya nambah satu category berjudul : Tulips from Amsterdam. Konon, life begin at 40. Mungkin “life” yang dimaksud adalah “brave to try something new”. Tapi seperti biasanya, I do it for my self. Sebagai salah satu tambahan coping kalau lagi stress. Jadi ceritanya akan dibuat cerbung dengan waktu tayang menggunakan rumus “saka” : sakainget, sakahoyong 😉 Mereka adalah salah satu pasangan favorit saya. Dua-duanya akademisi; suaminya profesor istrinya doktor. Suaminya berusia 71 tahun, istrinya 69 tahun. Mereka sudah pensiun. Saya senang mengamati relasi pasangan yang sudah sekian lama bersama. Pasangan ini sudah 40 tahun bersama ! Dan ketika bulan lalu saya menginap di rumah mereka di jantung kota Amsterdam, saya dapat “rejeki” mengamati relasi keseharian mereka di rumahnya. Biasanya, saya melihat relasi mereka saat mereka berkunjung ke Indonesia, dalam situasi formal-akademik. Di rumahnya, tentu relasi mereka lebih natural.
Mereka adalah salah satu pasangan favorit saya. Dua-duanya akademisi; suaminya profesor istrinya doktor. Suaminya berusia 71 tahun, istrinya 69 tahun. Mereka sudah pensiun. Saya senang mengamati relasi pasangan yang sudah sekian lama bersama. Pasangan ini sudah 40 tahun bersama ! Dan ketika bulan lalu saya menginap di rumah mereka di jantung kota Amsterdam, saya dapat “rejeki” mengamati relasi keseharian mereka di rumahnya. Biasanya, saya melihat relasi mereka saat mereka berkunjung ke Indonesia, dalam situasi formal-akademik. Di rumahnya, tentu relasi mereka lebih natural.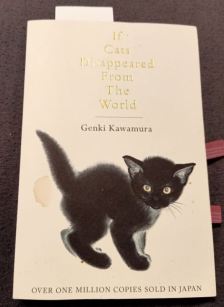 Salah satu buku “refreshing” yg saya baca saat di tanah Van Orange adalah bukunya Genki Kawamura. Pantesan buku ini best seller di Jepang & diterjemahkan ke beberapa bahasa. Keyen banget emang. Kisah fiksi yg ringan & lucu, tapi sesungguhnya itu adalah media untuk menyampaikan pesan filosofis yg bikin tercenung & berkaca2.
Salah satu buku “refreshing” yg saya baca saat di tanah Van Orange adalah bukunya Genki Kawamura. Pantesan buku ini best seller di Jepang & diterjemahkan ke beberapa bahasa. Keyen banget emang. Kisah fiksi yg ringan & lucu, tapi sesungguhnya itu adalah media untuk menyampaikan pesan filosofis yg bikin tercenung & berkaca2.
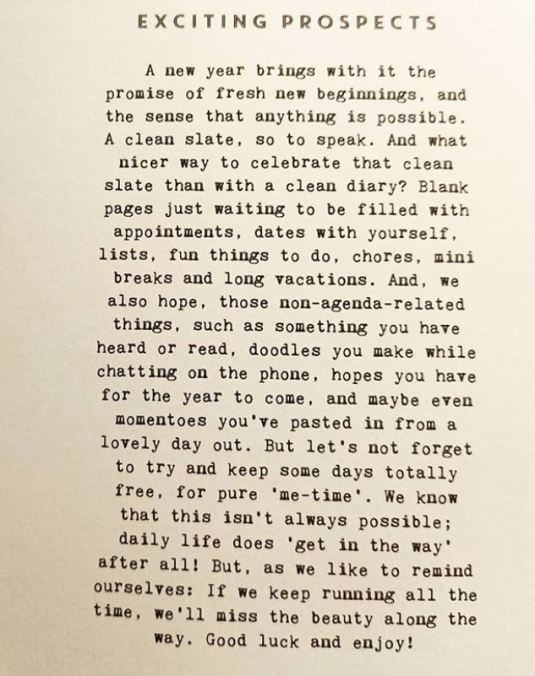





Recent Comments