Reaksi anak-anak saat saya tidak “konsen” mendengarkan cerita mereka :
Azka, si kelas 6 : “Ah, ibu mah gak dengerin….males ah” (pundung) //Umar, si kelas 3 : “Ibu, ibu teh dengerin mas Umar gak sih?” (marah) //Azzam, si dua tahun : “Ibu liat….ibu liat….ibu liat….” (sambil “menarik” dagu saya, menjadi menghadap dia) //Hana, si TK B : “Tatap mata saya….tatap mata saya…”
Itu adalah status yang saya tulis beberapa bulan lalu. Kejadian nyata. Lucu sih kalau dibaca, terutama reaksi Hana. Tapi sebenarnya harusnya saya malu dan menyesal. “Tidak didengarkan” itu, ternyata sangat “menyebalkan”. Tak percaya? coba saja hayati saat kita ingin banget bicara pada pasangan kita, trus pasangan kita “hare-hare”. Dengerin tapi sambil “main hape” (kalau istilah Hana). Atau dengerin tapi matanya tertuju ke layar laptop/TV, trus kalau kita tanya….ternyata tak ada satupun yang kita omongin yang “nempel”. Yang paling parah, adalah kalau dipanggil pun, susah banget nengoknya. Bayangkan, perilaku “menyebalkan” itu tanpa sadar kita lakukan saat anak butuh bicara pada kita. Pantas saja kalau kemudian anak-anak kita menjadi “tertutup” pada kita.
Mendengarkan. Tak semudah mengatakannya. Dalam bahasa Inggris, disebutnya Active Listening. Kenapa disebut aktif? Karena memang harus melakukan sesuatu, tak hanya “menerima”. Apa sih, yang kita harus lakukan sebagai tanda bahwa kita telah mendengar aktif atau mendengarKAN, bukan hanya mendengar?
Ada 3 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin secara aktif mendengarKAN apa yang dikatakan anak pada kita.
(1) SENSING
Sensing adalah proses dimana orangtua memperhatikan sinyal atau tanda yang diberikan anak saat berbicara. Kata-kata yang diucapkan, intonasi, kecepatan bicara, dan isyarat nonverbal.
Pada proses ini, ada 3 hal yang harus dilakukan orangtua. Daaaan….inilah “pintu gerbang” yang akan menentukan apakah anak akan terbuka pada kita atau tidak, apakah anak merasa dihargai dan dicintai atau tidak.
Tiga hal itu adalah :
• Postpone evaluation. Orangtua mencoba untuk berpikiran terbuka dan menunda tanggapan sampai anak selesai bercerita. Menunda tanggapan kita sampai anak selesai bercerita.
• Avoid interruptions. Mendengarkan keseluruhan cerita anak tanpa menginterupsinya. No intteruption !!
• Maintain interest. Orangtua benar-benar berniat untuk mendengarkan cerita anak dan menunjukkan keseriusan niatnya tersebut melalui gestur tubuh. Syarat yang paliiiiiiing minimal adalah, seperti yang dilakukan Azzam dan Hana : tubuh kita mengarah padanya, dan kita melakukan kontak mata dengan anak.
Sebelum lanjut ke poin berikutnya, mari kita pejamkan mata dan mengingat-ingat bagaimana sikap kita saat anak berbicara sesuatu yang “tak berkenan” buat kita. Hhhmmm….saya, punya satu pengalaman terkait poin ini. Banyak sih, tapi yang saya inget banget satu ini.
Suatu saat Umar bilang gini ke saya: “Bu, kenapa sih, rumah kita harus direnovasi jadi tingkat dua?”//jujur saya saya langsung kesel denger kata-katanya itu, mengingat sebelum renovasi dulu, dia yang paling ga sabar pengen cepet-cepet rumahnya dua lantai. Karena kesal itu, langsunglah saya memberikan tanggapan ….“Itu yang ibu gak suka dari Mas Umar. Mas Umar tuh gak pernah bersyukur. Dulu pengen banget rumahnya dua tingkat. Sekarang udah dua tingkat, masih mengeluh juga….” Kebayang kan, ekspresi saya saat mengatakan itu…Jadi saya gagal total melakukan proses MENDENGARKAN di tahap pertama. Saya langsung memberi evaluasi, langsung menginterupsi dan…boro2 menunjukkan interest kan….
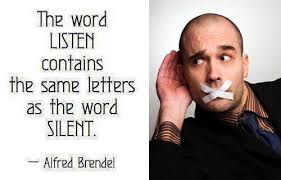 Beberapa menit kemudian saya sadar….kenapa ya, saya langsung memotong apa yang Umar sampaikan. Kenapa sebenernya dia ngomong gitu? Lalu saya pun bertanya pada dia…“Emang kenapa mas Umar tadi nanya gitu? mas Umar gak suka rumah kita jadi dua lantai? “. Dengan ekspresi ragu dia menjawab gini: “kan kata ibu renovasi itu mahal, ratusan juta. Nah, kenapa uang renovasi itu gak dipake umroh sekeluarga aja… kan kata ibu umroh sekeluarga juga 200 jutaan. Mas Umar pengen banget kita umroh sekeluarga. Jadi uangnya kan cukup buat umroh sekeluarga”…. Nyesssssss…..Nyesel ….hiks…coba kalau saya gak sempet sadar….keinginan yang baik itu, tak akan pernah saya ketahui. Coba kalau tadi saya mau mendengarkan. Tanpa judgement terlebih dahulu…..Setelah mengetahui apa sebenarnya ayng ingin ia sampaikan, selanjutnya saya jelaskan mengapa prioritasnya adalah renovasi rumah dibanding umroh sekeluarga.
Beberapa menit kemudian saya sadar….kenapa ya, saya langsung memotong apa yang Umar sampaikan. Kenapa sebenernya dia ngomong gitu? Lalu saya pun bertanya pada dia…“Emang kenapa mas Umar tadi nanya gitu? mas Umar gak suka rumah kita jadi dua lantai? “. Dengan ekspresi ragu dia menjawab gini: “kan kata ibu renovasi itu mahal, ratusan juta. Nah, kenapa uang renovasi itu gak dipake umroh sekeluarga aja… kan kata ibu umroh sekeluarga juga 200 jutaan. Mas Umar pengen banget kita umroh sekeluarga. Jadi uangnya kan cukup buat umroh sekeluarga”…. Nyesssssss…..Nyesel ….hiks…coba kalau saya gak sempet sadar….keinginan yang baik itu, tak akan pernah saya ketahui. Coba kalau tadi saya mau mendengarkan. Tanpa judgement terlebih dahulu…..Setelah mengetahui apa sebenarnya ayng ingin ia sampaikan, selanjutnya saya jelaskan mengapa prioritasnya adalah renovasi rumah dibanding umroh sekeluarga.
Itu ceritaku, apa ceritamu ? (nyontek iklan)
(2) EVALUATING
Evaluating adalah saat orangtua melakukan proses memahami maksud cerita, mengevaluasi, dan mengingat isi cerita anak. Setelah memberikan perhatian, maka kita mencoba menangkap konten pembicaraan si anak. Apa yang harus dilakukan orangtua di tahap ini? ada dua hal.
• Emphatize. Orangtua mencoba memahami dan sensitif terhadap perasaan, pemikiran, dan situasi anak. Nah, proses ini susah-susah gampang. Untuk anak yang lebih besar, kadang mereka tidak “to the point”. Kita jadi kesulitan menentukan apa yang penting dan apa yang gak penting buat anak. Namun rumus sederhananya adalah, kalau sesuatu itu secara durasi, atau frekuensi atau intensitasnya menonjol, berarti hal itu PENTING buat anak. Durasi? Anak ngomongin satu hal secara detiiiil….panjaaaaaang….. Frekuensi? topik itu seriiiiiiiiing banget dibicarakan anak. Intensitas? ekspresi emosi anak, intonasi anak….
• Organize information. Mengorganisasikan informasi hingga mendapatkan poin-poin penting dari cerita anak. Anak punya keterbatasan untuk bercerita runtut. Itulah sebabnya kita harus “sabar” menunda tanggapan kita dan biarkan anak menyelesaikan ceritanya.
 Saya punya satu contoh mengenai proses ini. Beberapa bulan lalu, sekolah Azka mengadakan eduwisata Ke Singapur. Ga wajib semua anak ikut…. yang mau aja. Azka bukan orang yang frontal menyatakan keinginannya. Waktu dia memberitahukan hal itu dan bertanya apakah ia bisa ikut atau tidak, setelah membicarakannya dengan Mas kami menyatakan Azka tidak usah ikut. Kami sampaikan bahwa meskipun kami ada uang 5 juta untuk kesana, namun menurut kami itu gak sepadan dengan apa yang akan didapat disana. Lalu ke luar negeri pertama kali, lebih asyik kalau bersama keluarga. Oke… Azka si penurut gak protes. Selanjutnya, setiap hari Azka selalu bicara tentang si Singapur itu. Cerita gimana teman-temannya izin untuk bikin pasport, gimana teman-temannya berencana ini-itu, cerita gimana kelasnya cuman 3 orang yang gak ikut…. Dari situ saya menangkap, sebenarnya Azka pengen banget ikut. Ketika saya tanya…”Kaka sebenernya pengen ikut ya?” dia bilang “Engga bu…lagian…cuman 2 hari satu malam….ternyata acaranya cuman jalan-jalan aja….lagian..seruan nanti sama keluarga”. Temans….jangan “lega” dulu kalau anak memberi reasoning akan sesuatu. Apalagi kalau dia “mengutip” kata-kata orang dewasa, bisa jadi itu pemahamannya dari sisi “kognitif” saja, tapi penghayatannya berbeda.
Saya punya satu contoh mengenai proses ini. Beberapa bulan lalu, sekolah Azka mengadakan eduwisata Ke Singapur. Ga wajib semua anak ikut…. yang mau aja. Azka bukan orang yang frontal menyatakan keinginannya. Waktu dia memberitahukan hal itu dan bertanya apakah ia bisa ikut atau tidak, setelah membicarakannya dengan Mas kami menyatakan Azka tidak usah ikut. Kami sampaikan bahwa meskipun kami ada uang 5 juta untuk kesana, namun menurut kami itu gak sepadan dengan apa yang akan didapat disana. Lalu ke luar negeri pertama kali, lebih asyik kalau bersama keluarga. Oke… Azka si penurut gak protes. Selanjutnya, setiap hari Azka selalu bicara tentang si Singapur itu. Cerita gimana teman-temannya izin untuk bikin pasport, gimana teman-temannya berencana ini-itu, cerita gimana kelasnya cuman 3 orang yang gak ikut…. Dari situ saya menangkap, sebenarnya Azka pengen banget ikut. Ketika saya tanya…”Kaka sebenernya pengen ikut ya?” dia bilang “Engga bu…lagian…cuman 2 hari satu malam….ternyata acaranya cuman jalan-jalan aja….lagian..seruan nanti sama keluarga”. Temans….jangan “lega” dulu kalau anak memberi reasoning akan sesuatu. Apalagi kalau dia “mengutip” kata-kata orang dewasa, bisa jadi itu pemahamannya dari sisi “kognitif” saja, tapi penghayatannya berbeda.
Karena saya menangkap Azka sebenernya pengen banget, pernah suatu saat saya duduk di samping dia, saya bilang…“kalau ibu jadi Kaka, ibu pengen banget ikutan. Kan kayaknya seru banget ya….sama temen-temen….Tapi uang 5 juta itu besar Ka…kalau dibeliin barang, kaka bisa depet laptop, bisa dapet kamera DSLR…(abahnya memang pernah berniat minta Azka milih: ke Singapur atau kamera…cuman sebagai mentri keuangan, saya tidak meng-acc-nya 😉 … ke Singapur cuman 2 hari. Laptop dan kamera…bisa dipake bertahun-tahun. Kalau dikasihin ke orang, bisa bikin anak yang gak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Bisa jadi modal usaha orang yang gak punya kerjaan….. Kadang-kadang yang kita inginkan itu, kalau kita pikirkan bukan pilihan yang terbaik”…begitu kata saya. Saya berusaha membuka sudut pandang anak yang biasanya melihat satu hal sari satu sudut pandang aja: sudut pandang dirinya. Gak tau tujuan saya berhasil atau tidak hehe…Sejak saat itu, Azka masih terus cerita soal Singapur. Tapi dengan didengarkan saja, sebenarnya kebutuhannya cukup terpenuhi.
(3) RESPONDING
Responding adalah saat dimana orangtua menunjukkan isyarat perilaku untuk mendukung proses komunikasi selama anak bercerita. Proses yang perlu dilakukan orangtua pada tahap ini adalah :
• Show interest. Orangtua memperlihatkan ketertarikan terhadap cerita anak dengan mempertahankan kontak mata dan memberi komentar singkat seperti “Oh”, “Hmm”, atau “Lalu?”, atau “masa?” di jeda cerita yang tepat. Juga ortu menunjukkan respons yang “nyambung”. Teruatama untuk anak yang lebih kecil, yang suka cerita dengan ekspresif. Bukan tanpa tantangan …. karena kadang karena keterbatasan anak, ceritanya gak kita tangkap seutuhnya. Kalaupun berhasil kita tangkap, aduuuh….. kadang ceritanya “gak penting banget”. Hana yang sering kayak gini…misalnya dia dengan antusias cerita kalau tadi temennya jawab apa….gitu…buat dia sih lucu banget…sampai dia ekspresif banget dan berulang-ulang ceritanya. Buat kita? kadang “garing” banget. Tapi kalau kita “potong” dengan tak memberikan respons yang sesuai, tak ikutan tersenyum, ketawa, membelalakkan mata…atau kita bilang “apa lucunya de?“….yakinlah itu cara efektif uantuk “memutuskan hubungan” dengan anak.
• Clarify the message. Orangtua mengungkapkan ulang inti cerita anak sambil menyamakan pemahaman dengan anak. Beberapa kali, kalau saya lagi riweuh, saya pura-pura dengerin dengan memberikan respons seperti …”oh gitu…masa…terus gimana…”. Tapi ternyata kepura-puraan saya akhir-akhir ini sering ketahuan Azka. Dia suka nanya…“apa coba bu, yang Kaka ceritain tadi”... dan gilenya….beneran …sering kali saya gak bisa jawab…jadi yang tadi Azka katakan saya denger…tapi kayaknya cuman gelombang suara aja, gak mampir untuk dimaknakan di otak ini…Kalau udah gini, maka Azka akan bilang : “tuh kan, ibu mah ga dengerin”. Kalau dia lagi good mood, saya minta ulangi lagi dia mau. Tapi kalau lagi bete, dia langsung masuk kamar dan nulis diary hiks hiks…saya bisa nebak apa yang dia tulis 😉
Temans, we are not super mom. Dan kita gak dituntut untuk itu. We are human. Seringkali kita tidak bisa mendengarkan anak, bukan karena kita lagi sibuk wa-an bahas copras-capres. Seringkali kita tidak memberikan respons yang sesuai pada anak, bukan karena kita merasa terganggu karena lagi mantengin barang-barang online. Seringkali kita tak bisa menanggapi dan memberi perhatian pada anak karena kita sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk keluarga. Atau sedang ada pekerjaan yang mendesak.
Seperti yang saya alami 2 minggu lalu. Saya mendapat “amanah” baru di kampus. Waktu itu ada koordinasi yang mendesak. Hana jemput saya. Lalu di mobil dia bicara banyaaak. Saya harus koordinasi yang urgent. Saya denger dia bilang; “ibu, jangan ceting aja…dengerin teteh”. Saya bilang : “Teh, ibu ini ada yang penting banget, kalau ibu gak jawab sekarang, nanti tante **** harus pulang malem banget, kasian kan tante **** punya anak kecil. jadi ibu harus bantuin dia, lewat ngobrol ini”. Apakah ia mengerti? Beberapa menit kemudian, dia menyodorkan sebuah gambar. Isinya adalah orang dewasa lagi pegang hape, dan anak kecil yang nangis. Lalu ada tanda silang (x) di gambar hapenya. Setelah saya beres koordinasi, saya tanya…ini gambar apa? dia bilang “ini gambar ibu yang lagi ngehape terus. Ini gambar kakak yang gak suka ibu ngehape terus. Kakanya sedih jadi nangis”.
Mungkin teman-teman gak persis ngalamin peristiwa ini. Tapi mungkin pernah mendapat “protes keras” dari anak-anak. It’s oke….yang penting gimana kita memperbaikinya. Waktu itu, saya peluk Hana. Saya jelaskan sekali lagi dengan lebih detil situasinya. Lalu saya jelaskan situasi-situasi dimana saya suka mendengarkan dia dengan sepenuh hati. Saya berharap dia paham bahwa situasinya berbeda. Apakah itu cukup? saya pikir cukup. Tapi ternyata tdak saudara-saudara ! besoknya, dia masih mengungkit-ungkit hal itu…dia “nulis surat”, diselipin di agenda saya, trus bilang “ibu, ini surat isinya adalah, ibu jangan ngehape terus. ibu harus dengerin teteh”. Waktu saya bilang “kan ibu udah jelaskan kemarin…” dia bilang : “Tapi ibu belum minta maaf”….
Baiklah…ternyata eh ternyata…”minta maaf” adalah hal penting buat seorang anak. Tak hanya anak umur 5 tahun. Saya pernah mendengar beberapa anak remaja dan dewasa yang begitu amat ingat kesalahan ortunya, dan sangat ingat pula kalau orangtuanya belum meminta maaf. Jadilah saya waktu itu bilang sambil peluk Hana, “ibu minta maaf ya….”.…. ternyata saya dapat hadiah dari kesediaan saya minta maaf itu…sebuah gambar ynag isinya orang dewasa sedang pelukan sama anak kecil, dengan wajah tersenyum:)
Mendengarkan. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Karena ia tak mudah, maka efeknya pun tak kecil. Menumbuhkan perasaan dihargai dan dicintai. Menumbuhkan dan menguatkan hubungan emosi. Dan good news-nya, kemampuan ini bisa dipelajari ! practice makes perfect.
 Saya sering denger keluhan orangtua : “Anak saya gak mau dengerin saya”. Mungkin, anak kita tak mau mendengar karena gak dapet contoh gimana caranya mendengarkan itu. Karena ortunya susah “nengok” kalau diajak bicara, maka begitulah anak belajar jadi dia pun susah diajak bicara “face to face”. Karena kita biasa memotong bicara anak, mungkin anak kita merasa tidak salah kalau dia langsung “nyahut” kalau diomongin sesuatu.
Saya sering denger keluhan orangtua : “Anak saya gak mau dengerin saya”. Mungkin, anak kita tak mau mendengar karena gak dapet contoh gimana caranya mendengarkan itu. Karena ortunya susah “nengok” kalau diajak bicara, maka begitulah anak belajar jadi dia pun susah diajak bicara “face to face”. Karena kita biasa memotong bicara anak, mungkin anak kita merasa tidak salah kalau dia langsung “nyahut” kalau diomongin sesuatu.
Semoga kita dimampukan untuk tak hanya berbicara dengan baik, tapi juga mendengarkan dengan baik.
 Saya pernah cerita, ada satu momen yang saya simpan sebagai salah satu momen terindah dalam hidup saya, yaitu saat belasan tahun lalu, di tengah keheningan itikaf jam 2 dinihari, seorang anak laki-laki berusia 7 tahunan asyik melantunkan surat Arrahman. Malam tadi saya menemukan momen serupa. Saat sebagian besar orang dewasa telah terlelap, seorang anak perempuan 7 tahun-an asyik tilawah dengan Qur’an kecil di tangannya.
Saya pernah cerita, ada satu momen yang saya simpan sebagai salah satu momen terindah dalam hidup saya, yaitu saat belasan tahun lalu, di tengah keheningan itikaf jam 2 dinihari, seorang anak laki-laki berusia 7 tahunan asyik melantunkan surat Arrahman. Malam tadi saya menemukan momen serupa. Saat sebagian besar orang dewasa telah terlelap, seorang anak perempuan 7 tahun-an asyik tilawah dengan Qur’an kecil di tangannya.

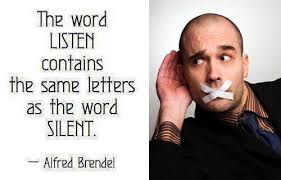




Recent Comments