Salah satu quality time yang baru saya sadari antara saya dan anak-anak, adalah bada shubuh. Kalau si abah ada di rumah, pulang dari mesjid bersama si bujang kecil, biasanya si abah memutar ceramah pagi dari beberapa ustadz, dan kami dengarkan sambil melakukan aktiiftas masing-masing. Anak-anak mandi, saya nyiapin sarapan atau panik ngerjain deadline yang belum beres haha. Nah, kalau si abah gak ada, bada subuh sepulang si bujang kecil dari masjid, dengan masih bersarung-bermukena, kami suka tidur-tiduran di musholla. Si bungsu dan di gadis kecil biasanya minta dipeluk lagi dengan alasan klise; “kedinginan”.
Nah….sambil itu, biasanya kami ngobrol macem-macem. Kadang saya ngasih nasehat…. paling sering bahas arti doa sesudah sholat. Sampai-sampai anak-anak sering nyela …iya bu..udah tau…bla..bla..bla… kan? Tapi saya gak mau kalah. Selalu saya kasih tambahan contoh konkrit terkait doa itu. Misal doa “allahumma inna as’aluka salamatan fid diiin….. “. Apa sih maksud “selamat dalam agama itu?” setiap hari banyak contoh konkrit yang berbeda-beda. “waafiyatan fil jasad….” banyak banget contoh yang berbeda-beda tiap hari. Pengalaman saya menengok teman, pengalaman anak-anak mengenai beragam kuman dan penyakit…. dan selanjutnya. Biasanya dari contoh ilustrasi doa itu, berlanjut obrolan panjaaaaaang… maklum interpretasi dari anak umur 14, 11, 8 dan 5, seringkali liar dan tak terduga. Dari yang super ilmiah sampai yang super kocak dan polos. Yang kocak hampir pasti dari si gadis kecil yang sering mengutip pernyataan tokoh kartun favoritnya, si Juki kkk
Pagi ini, obrolan di musholla kami adalah obrolan yang super duper berat; obrolan yang saya takuti selama ini. Obrolan mulai dari tema “ciuman”. Dimulai dengan si bungsu yang bilang: “bu, ayo kita ciuman menikah”. Maksudnya bibir ke bibir. Karena dia masih kecil, saya cium dia, lalu cium seluruh wajahnya. Seneng banget si bungsu mengabsen semua bagian wajahnya untuk dicium. Mata? hidung? nonong? nanti dia akan iseng lanjut ke …. ketek….
Nah, si bujang kecil menyela: “bu, setelah nikah ibu dan abah ciuman kan? ciuman teh caranya punya bayi kan?”. Si gadis kecil menyela: “Bukan atuh mas, kata di buku Aku Tahu Asal Usulku, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu bertemu saat ayah dan ibu menyatukan tubuhnya”. Si bujang kecil lanjut lagi: “iya menyatukan tubuh teh gimana? ciuman kan? kan sel sperma teh diproduksi di testis, gimana bu nyampe di mulut. Trus emang sel telur ibu di mulut? bukannya di rahim? rehim teh di perut kan?”
Oh My God…. tau gak …pertanyaan itu, pertanyaan tentang “bagaimana cara sel sperma ketemu sel telur”, itu adalah pertanyaan yang paling saya takuti sejak masih punya satu anak. Kenapa? karena saya gak tau dan gak yakin gimana cara jawabnya. Kalau dikasihtau bahwa caranya adalah penis masuk ke vagina…. jujur saya gak siap dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau menghindar gak menjawab, gampang banget buat anak-anak ketik cari tau di google, takutnya yang keluar malah gambar yang ajaib.
“Nanti Mas akan belajar di pelajaran biologi Mas” jawab saya. Bu Guru….Pak Guru…..saya mengandalkanmuuuuuu hehe… “Tapi Mas mau tau sekarang bu….” jawabnya mendesak. Haduuuuh… udah bahagia banget si sulung gak nanya tentang itu. Eh….kejadian juga ditanya si bujang kecil yang memang super kritis.
“Nanti ibu tanya tanteu XXX ya…Tanteu XXX temen ibu yang belajar tentang itu”. Jawab saya. Sukurlah pembicaraan akhirnya beralih ke topik baju yang akan dipake si gadis kecil di pentas profesi dua minggu lagi. Dia memilih profesi pelukis dari pilihan profesi2 yang tersedia. Sejak kemarin saya memeras pikiran gimana ya baju pelukis itu? udah ada beberaap ide, tapi sebagai orang yang tidak kreatif, saya takut ide itu garing ….
Maka, setengah enam tadi, saya bukan laptop dan kirim wa panjang lebar pada dua teman saya. Satu teman saya, peneliti di bidang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas. Melalui studi-studinya di Bandung, dia akan tau betul gimana caranya jawab pertanyaan si bujang kecil yang tidak berpotensi mengarah pada rasa penasaran yang tersalur pada cara negatif. Saya inget banget obrolan-obrolan kami: “anak tuh butuh informasi tentang seksualitas. Mereka tuh butuh orangtua menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi kalau kita gak siap, pertanyaan itu akan mereka terus cari jawabannya. Dan dari internet atau dari teman, informasinya gak selalu baik dan benar”. Itulah sebabnya ia bersama tim nya menyusun program eduksi seksualitas untuk remaja di kota Bandung lewat sekolah.
Teman kedua yang saya wa panjang lebar adalah teman saya designer yang super duper kreatif. Tentang design baju pelukis si gadis kecil.
Ahh….. dulu, saya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mengatakan : “Kamu harus mandiri. Harus bisa semuanya sendiri. Itu artinya kamu hebat. Kalau kamu minta tolong orang lain, berari kamu lemah”. Gak salah sih. Tapi saya bersyukur, perjalanan hidup saya selanjutnya mengenalkan saya pada prinsip yang jauh lebih mempesona. “interdependensi. Saling tergantung”. Saya inget banget, pertama kali saya baca di Salman dari bukunya Covey. Asumsi yang mendasarinya sangat “rendah hati” menurut saya: bahwa di dunia yang akan datang, tantangan sedemikian kompleks sehingga tak satu pun dari kita punya kapasitas untuk menghadapinya kompleksitas tersebut sendirian. Sehebat apapun kita. Maka itulah, kita kuasai satu hal secara mendalam, lalu kita bersinergi dengan orang lain yang punya keahlian berbeda. Itulah caranya kita menaklukkan tantangan.
Prinsip itu, memang ditujukan untuk dunia profesi. Tapi sebagai seorang ibu, prinsip itu sangat amat aplikatif. Kita tak harus jadi “ibu hebat”; “ibu super”; … kita jadi ibu yang …manusiawi aja. Punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan yang kita miliki, kita bagikan; siapa tau bisa membantu ibu lain yang gak punya kelebihan itu. Kekurangan yang kita miliki, kita “tambal” dengan meminta bantuan pada ibu lain yang punya kelebihan dalam hal itu.
 Dengan kompleksitas peran kita sebagai ibu, “harus tau segalanya”, “harus menguasai segalanya”, “harus mengajarkan semuanya”, adalah “misi bunuh diri” buat saya. Dan kita gak akan banyak belajar hal baru dengan berprinsip demikian. Mari bekerjasama. Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan itu adalah tanda penghargaan pada orang lain dan latihan kerendahan hati. Tanya pada mereka yang ahli di bidangnya. Minta tolong pada mereka yang memiliki keterampilan di bidangnya. Hasilnya? tak hanya anak kita yang akan belajar, tapi juga kita. Tak hanya anak kita yang dapat pengetahuan dan keterampilan baru, tapi kita juga. Jadi kita berkembang bersama.
Dengan kompleksitas peran kita sebagai ibu, “harus tau segalanya”, “harus menguasai segalanya”, “harus mengajarkan semuanya”, adalah “misi bunuh diri” buat saya. Dan kita gak akan banyak belajar hal baru dengan berprinsip demikian. Mari bekerjasama. Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan itu adalah tanda penghargaan pada orang lain dan latihan kerendahan hati. Tanya pada mereka yang ahli di bidangnya. Minta tolong pada mereka yang memiliki keterampilan di bidangnya. Hasilnya? tak hanya anak kita yang akan belajar, tapi juga kita. Tak hanya anak kita yang dapat pengetahuan dan keterampilan baru, tapi kita juga. Jadi kita berkembang bersama.
Saya sudah menerapkan prinsip ini, dan PAS buat saya. Anak-anak kebagian siapin makan buat temen-temen sekelasnya; minta tolong temen yang bikinin bento super duper lutu. Anak senang, saya senang, teman saya senang. Saya paling gak bisa mendongeng. Saya bawa ke temen saya yang jago mendongeng. Anak saya kagum, saya juga kagum. Menggambar? haduuuh….nilai menggambar saya waktu SMA 50 dari 100 saking bututnya. Saya bawa ke temen yang bisa ngajarin cara gambar dengan mudah dan sederhana. Anak saya belajar hal baru, saya juga. Anak-anak tanya mainan yang seru? saya tanya temen saya yang jualan mainan. Anak cari media belajar yang asik? saya tanya ke temen saya yang seneng dan banyak tau tentang multimedia. Banyaaak banget yang kita bisa sinergikan dengan para emak yang lain.
Itulah hakikat bahwa kita Bukan Emak Biasa. Btw, kalau mau pesan, stok baru buku BUKAN EMAK BIASA datang hari ini. Mangga bisa wa ke no 0812-1416-2629 dengan menyebutkan nama, jumlah pemesanan dan alamat lengkap. Haha….kesempatan dalam kesempitan 😉
Pokoknya mah ..semangat emaks!!!! You are not alone…..
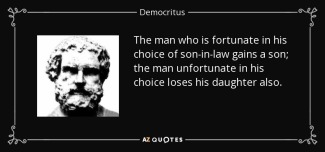 Buat saya pribadi, pembicaraan tentang calon mantu ini selain menghibur, memfasilitasi kalibrasi nilai, juga menumbuhkan kesadaran … mulai berdoa untuk memohon pasangan yang baik bagi anak-anak saya. Juga mulai berikhtiar mendidik anak-anak saya untuk menjadi individu-individu yang matang, baik dan benar. Kalau sudah demikian, kita bisa percaya bahwa dia akan memilih pasangan yang “frekuensi”nya tak beda jauh dengannya.
Buat saya pribadi, pembicaraan tentang calon mantu ini selain menghibur, memfasilitasi kalibrasi nilai, juga menumbuhkan kesadaran … mulai berdoa untuk memohon pasangan yang baik bagi anak-anak saya. Juga mulai berikhtiar mendidik anak-anak saya untuk menjadi individu-individu yang matang, baik dan benar. Kalau sudah demikian, kita bisa percaya bahwa dia akan memilih pasangan yang “frekuensi”nya tak beda jauh dengannya. Jadi, trust itu bukan suatu hal yang saklek. Hitam putih. Ya atau tidak. Trust itu adalah kadar. Kadarnya kadang bertambah, kadang berkurang. Di titik manapun kita berada, kita selalu punya kesempatan untuk meningkatkan kadarnya. Tapi kita harus ingat, menjaga kepercayaan itu sama sulitnya dengan mempercayai seseorang. Maka, kalau anak-anak kita berjuang mengumpulkan keberanian untuk mempercayai kita, maka kita pun harus mengimbanginya dengan mengumpulkan kebijaksanaan menjaga kepercayaan anak kita. Anak berani terbuka, kita bijaksana menghargai, anak semakin terbuka, kita semakin bijaksana menghargai, teruuuus….itulah relationship. Hubungan.
Jadi, trust itu bukan suatu hal yang saklek. Hitam putih. Ya atau tidak. Trust itu adalah kadar. Kadarnya kadang bertambah, kadang berkurang. Di titik manapun kita berada, kita selalu punya kesempatan untuk meningkatkan kadarnya. Tapi kita harus ingat, menjaga kepercayaan itu sama sulitnya dengan mempercayai seseorang. Maka, kalau anak-anak kita berjuang mengumpulkan keberanian untuk mempercayai kita, maka kita pun harus mengimbanginya dengan mengumpulkan kebijaksanaan menjaga kepercayaan anak kita. Anak berani terbuka, kita bijaksana menghargai, anak semakin terbuka, kita semakin bijaksana menghargai, teruuuus….itulah relationship. Hubungan. Ya, kita adalah para ibu. Penjelmaan rahman-rahimNya Allah di muka bumi. Kita akan terus belajar untuk menjadi peka saat tembok ketidakpercayaan mulai tumbuh diantara kita dan anak-anak. Kita akan terus berjuang untuk menjadi berani menghancurkan tembok itu dengan mengakui kesalahan dan bersabar menunggu kepercayaan itu tumbuh kembali. Sehingga anak-anak kita, selalu percaya bahwa di dunia ini, ada seseorang yang selalu menyediakan pelukan. Tempat ia bisa membuka dirinya tanpa topeng apapun. Sejauh apapun ia pergi, seburuk apapun yang ia lakukan, seberat apapun yang ia alami; ia tak akan putus asa, ia tak akan patah arang. Karena ia yakin punya tempat untuk “kembali”.
Ya, kita adalah para ibu. Penjelmaan rahman-rahimNya Allah di muka bumi. Kita akan terus belajar untuk menjadi peka saat tembok ketidakpercayaan mulai tumbuh diantara kita dan anak-anak. Kita akan terus berjuang untuk menjadi berani menghancurkan tembok itu dengan mengakui kesalahan dan bersabar menunggu kepercayaan itu tumbuh kembali. Sehingga anak-anak kita, selalu percaya bahwa di dunia ini, ada seseorang yang selalu menyediakan pelukan. Tempat ia bisa membuka dirinya tanpa topeng apapun. Sejauh apapun ia pergi, seburuk apapun yang ia lakukan, seberat apapun yang ia alami; ia tak akan putus asa, ia tak akan patah arang. Karena ia yakin punya tempat untuk “kembali”.
Recent Comments